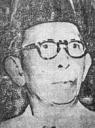 Sebagai tokoh
pendidikan, Ki Hajar Dewantara tidak seperti Ivan Illich atau
Rabrindranath Tagore yang sempat menganggap sekolah sebagai siksaan yang
harus segera dihindari. Ki Hajar berpandangan bahwa melalui pendidikan
akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka
serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan
kebangsaan dan berlanggam kebudayaan.
Sebagai tokoh
pendidikan, Ki Hajar Dewantara tidak seperti Ivan Illich atau
Rabrindranath Tagore yang sempat menganggap sekolah sebagai siksaan yang
harus segera dihindari. Ki Hajar berpandangan bahwa melalui pendidikan
akan terbentuk kader yang berpikir, berperasaan, dan berjasad merdeka
serta percaya akan kemampuan sendiri. Arah pendidikannya bernafaskan
kebangsaan dan berlanggam kebudayaan.
Seorang
tokoh seperti Ivan Illich pernah berseru agar masyarakat bebas dari
sekolah. Niat deschooling tersebut berangkat dari anggapan Ivan
Illich bahwa sekolah tak ubahnya pabrik yang mencetak anak didik dalam
paket-paket yang sudah pasti. “…bagi banyak orang, hak belajar sudah
digerus menjadi kewajiban menghadiri sekolah”, kata Illich. Demikian
pula halnya dengan Rabindranath Tagore yang sempat menganggap sekolah
seakan-akan sebuah penjara. Yang kemudian ia sebut sebagai “siksaan yang
tertahankan”.
Ada
benarnya ketika setiap pendidikan harus mampu mengarah dan mengubah
status quo. Dan ini tidak berarti benar ketika menganggap sekolah tidak
penting. Anak-anak dengan senang hati, umumnya masih berangkat ke sana.
Kita, dan mereka, tahu; bukan mata pelajaran serta ruang kelas itu yang
membikin mereka betah. Melainkan teman dan pertemuan. Bisa saja, Illich
dan Tagore keliru. Sekolah juga keliru bila ia tidak tahu diri bahwa
peranannya tidak seperti yang diduga selama ini. Ia bukan
penentu gagal tidaknya seorang anak. Ia tak berhak menjadi perumus masa
depan.
Namun,
banyak kalangan sering menyejajarkan Ki Hajar Dewantara dengan
Rabindranath Tagore, seorang pemikir, pendidik, dan pujangga besar kelas
dunia yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional
India, karena mereka bersahabat dan memang memiliki kesamaan visi dan
misi dalam perjuangannya memerdekakan bangsanya dari keterbelakangan.
Tagore
dan Ki Hajar sama-sama dekat dengan rakyat, cinta
kemerdekaan dan bangga atas budaya bangsanya sendiri. Tagore pernah
mengembalikan gelar kebangsawanan (Sir) pada raja Inggris sebagai protes
atas keganasan tentara Inggris dalam kasus Amritsar Affair. Tindakan
Tagore itu dilatarbelakangi kecintaannya kepada rakyat. Begitu juga
halnya dengan ditanggalkannya gelar kebangsawanan (Raden Mas) oleh Ki
Hajar. Tindakan ini dilatarbelakangi keinginan untuk lebih dekat dengan
rakyat dari segala lapisan. Antara Ki Hajar dengan Tagore juga merupakan
sosok yang sama-sama cinta kemerdekaan dan budaya bangsanya sendiri.
Dipilihnya bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai medan perjuangan
tidak terlepas dari “strategi” untuk melepaskan diri dari belenggu
penjajah. Adapun logika berpikirnya relatif sederhana; apabila rakyat
diberi pendidikan yang memadai maka wawasannya semakin luas, dengan
demikian keinginan untuk merdeka jiwa dan raganya tentu akan semakin
tinggi.
Di
barat, Paulo Freire hadir dengan konsep pendidikan pembebasan. Di sini,
Ki Hajar Dewantara menjadi pahlawan pendidikan nasional karena
pendidikan sistem among yang ia kembangkan di taman siswa. Ungkapannya
sangat terkenal; “tut wuri handayani”, “ing madya mangun karsa”, dan
“ing ngarsa sung tulada”. Istilah inipun tak hanya populer
di kalangan pendidikan, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan lain.
Siapakah
sebenarnya tokoh pelopor pendidikan bangsa ini?
Siapa
sih, yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Pejuang gigih,
politisi handal, guru besar bangsa, pendiri Taman Siswa, memang sudah
diakui oleh sejarah. Tapi sebagai pribadi yang keras tapi lembut, ayah
yang demokratis, sosoknya yang sederhana, penggemar barang bekas, belum
banyak orang tahu. Bahkan bagaimana tiba-tiba dia dipanggil dengan nama
Ki Hajar Dewantara juga belum banyak yang tahu.
Tokoh
peletak dasar pendidikan nasional ini terlahir dengan nama Raden Mas
Soewardi Soeryaningrat, dilahirkan di Yogyakarta pada hari Kamis,
tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton
Yogyakarta. Pendidikan dasarnya diperoleh di Sekolah Dasar ELS (sekolah
dasar Belanda) dan setelah lulus, ia meneruskan ke STOVIA (sekolah
kedokteran Bumi putera) di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai.
Kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedya
Tama, Midden Java, De Express, Oetoesan
Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara.
Ia tergolong penulis tangguh pada masanya; tulisan-tulisannya sangat
tegar dan patriotik serta mampu membangkitkan semangat antikolonial
bagi pembacanya.
Selain
menjadi seorang wartawan muda R.M. Soewardi juga aktif dalam organisasi
sosial dan politik, ini terbukti di tahun 1908 dia aktif di Boedi
Oetama dan mendapat tugas yang cukup menantang di seksi propaganda.
Dalam seksi propaganda ini dia aktif untuk
mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada
waktu itu mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan
bernegara.
 Keras tapi Tidak
Kasar. Inilah ciri khas kepribadian Ki Hajar yang diakui rekan-rekan
sejawatnya. Kras maar nooit grof, keras namun tidak pernah
kasar. Kesetiaan pada sikapnya ini terlihat jelas pada setiap kiprahnya.
Keras tapi Tidak
Kasar. Inilah ciri khas kepribadian Ki Hajar yang diakui rekan-rekan
sejawatnya. Kras maar nooit grof, keras namun tidak pernah
kasar. Kesetiaan pada sikapnya ini terlihat jelas pada setiap kiprahnya.
Ketika
partainya, Partai Hindia atau Indische Partij (IP) dibredel pemerintah
Belanda (1912), dia tidak putus asa. Kritik pedas kepada penjajah juga
dilancarkan lewat artikelnya dalam de Express November 1913, berjudul Als
ik eens Nederlander was (Seandainya saya orang Belanda). Dengan
sindiran tajam, tulisan itu menyatakan rasa malunya merayakan hari
kemerdekaan negerinya dengan memungut uang dari rakyat Hindia yang
terjajah. Soewardi bahkan mengirim telegram kepada Ratu Belanda berisi
usulan untuk mencabut pasal 11 RR (Regerings Reglement – UU Pemerintahan
Negeri Jajahan) yang melarang organisasi politik di Hindia-Belanda.
Karuan saja, akibat tulisan itu Ki Hajar dibuang ke Belanda pada Oktober
1914. Padahal dia baru saja mempersunting R.A. Sutartinah. Jadi,
terpaksa dia harus berbulan madu di pengasingan.
Dalam
masa pembuangan itu tidak dia sia-siakan untuk mendalami masalah
pendidikan dan pengajaran, sehingga berhasil memperoleh Europesche Akte.
Setelah kembali ke tanah air di tahun 1918, ia mencurahkan perhatian di
bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih
kemerdekaan. Diwujudnyatakan bersama rekan-rekan seperjuangan dengan
mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau lebih
dikenal dengan Perguruan Nasional Tamansiswa pada 3 Juli 1922, sebuah
perguruan yang bercorak nasional.
Perguruan
nasional Taman Siswa mencoba memadukan model pendidikan barat dengan
budaya-budaya negeri sendiri. Namun, kurikulum pemerintah Hindia Belanda
tidak diajarkan, karena garis perjuangan Ki Hajar bersifat
non-kooperasi terhadap pemerintah kolonial. Sifatnya mandiri.
Tak
hanya dalam bersikap, secara fisikpun Ki Hajar memiliki keberanian yang
mencengangkan. Ini terkuak dalam peristiwa rapat umum di Lapangan Ikada
(sekarang Monas), 19 September 1945. Saat itu pemerintah R.I.
menghadapi tantangan, apakah presiden dan jajaran kabinetnya berani
menembus kepungan senjata tentara Jepang di sekeliling lapangan.
Sebagian menuntut Presiden, Wapres, dan segenap anggota kabinet hadir di
Lapangan Ikada agar tidak mengecewakan rakyat. Yang lain menolaknya
denga n pertimbangan keselamatan.
Akhirnya,
semua sepakat untuk hadir. Tapi, siapa menteri yang harus membuka jalan
memasuki Lapangan Ikada, sebelum rombongan presiden. Karena ada
kemungkinan Jepang membantai rombongan menteri yang pertama masuk Ikada
untuk mencegah keberhasilan Pemerintah RI menyatakan eksistensinya
kepada rakyat dan dunia internasional. Pada saat kritis inilah sebagai
Menteri Pengajaran Ki Hajar unjuk keberanian. Bersama Menlu Mr. Achmad
Subarjo, Mensos Mr. Iwa Kusuma Sumantri, ia menyediakan tubuhnya menjadi
tameng. Padahal bapak enam anak itu bisa dibilang tak lagi muda. Ketika
diingatkan oleh Sesneg Abdul Gafur Pringgodigdo, “Ingat, Ki Hajar ‘kan
sudah tua.” “Justru karena itulah, mati pun tidak mengapa,” jawab Ki
Hajar enteng.
Sebagai
Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan pendiri
Tamansiswa, Ki Hajar memang tidak sendirian berjuang menanamkan jiwa
merdeka bagi rakyat melalui bidang pendidikan. Namun telah diakui dunia
bahwa kecerdasan, keteladanan dan kepemimpinannya telah menghantarkan
dia sebagai seorang yang berhasil meletakkan dasar pendidikan nasional
Indonesia. Ki Hajar bukan saja seorang tokoh dan pahlawan
pendidikan ini tanggal kelahirannya 2 Mei oleh bangsa Indonesia
dijadikan hari Pendidikan Nasional, selain itu melalui surat keputusan
Presiden RI no. 395 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959 Ki
Hajar ditetapkan sebagai pahlawan Pergerakan Nasional. Penghargaan
lainnya yang diterima oleh Ki Hajar Dewantara adalah gelar Doctor
Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada di tahun 1957.
Orang
seringkali lupa, semboyan tutwuri handayani adalah bagian
dari kesatuan yang lengkapnya berbunyi, ing ngarso sung tulada, ing
madya mangun karsa, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan,
di tengah menghidupkan gairah, di belakang memberi pengarahan. Mungkin,
peristiwa di atas sekaligus bisa memberi jawaban, apakah yang harus
dilakukan oleh seorang pemimpin kalau anak buahnya terancam
bahaya.
Masalah
pendidikan memang rumit. Terlebih lagi jika anggaran dananya juga
sedikit. Program pendidikan yang dicita-citakan bangsa ini begitu besar,
namun kesadaran pendidikannya masih sering tercium aroma komersial.
Akibatnya, nilai-nilai pendidikan tergeser begitu jauh dari pusarannya.
(-o0o-)
(-o0o-)
Sumber: Bulletin
Folder Buku vol.4/Th.I/Mei 2003
folder BUKU:
menyemarakkan budaya membaca
adalah media
alternatif yang memberikan informasi tentang dunia per-buku-an dan
seluk-beluknya. Wadah untuk menampung kreativitas berolah-pikir dalam
mengupas gagasan-gagasan sebuah buku.
Penanggungjawab:
komunitasKECIL
Alamat: Kepuh GK
3 / 1023 Yogyakarta 55222 Telp. 0274 – 545563
E-mail: folderbuku@yahoo.com
Milis:folderbuku@yahoogroups.com
“Sekiranya
aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta
kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar
dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak
pantas untuk menyuruh si inlander
memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk
menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang
kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu!
Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan
kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa
inlander diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang ia sendiri
tidak ada kepentingan sedikitpun”.

















0 komentar:
Posting Komentar